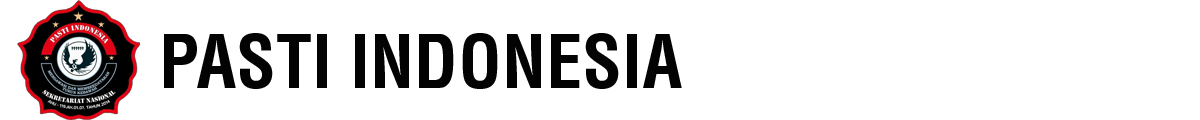Dalam sebuah survei ketika anak-anak NTT ditanya apa cita-citanya. Mereka menjawab riang mulai dari astronot, guru, hingga hansip. Semangat semacam ini terasa jika kita keliling NTT, di pelosok NTT kita temukan anak-anak berseragam SD yang gigih ingin pergi ke sekolah ramah melambaikan tangan,
ataupun serempak mengucapkan ‘selamat siang’ atau ‘selamat pagi’ ketika berpapasan. Namun kapan semangat mereka pudar, dan kapan mereka berhenti bermimpi?
Berdasarkan data BPS NTT rata-rata anak-anak NTT putus sekolah di SMP kelas satu. Mungkin orang bisa berkilah karena fasilitas SMP dan SMA minim di daerah pelosok NTT, tetapi bagaimana menjelaskan kondisi di Kabupaten Sumba Tengah yang rata-rata anak putus sekolah di kelas lima SD. Kenapa mereka tidak melanjutkan belajar?
Ya, kita sedang tidak berbicara sekolah-sekolah elit di NTT di Kota Kupang maupun beberapa kota kabupaten yang anak-anaknya telah diajarkan berbahasa inggris, mandarin, arab sejak usia dini, bahkan anak-anak yang telah diajar untuk menulis bahasa computer sejak belia. Tetapi kita sedang berbicara soal anak-anak NTT pada umumnya. Anak-anak rakyat jelata.
Meskipun tak semua orang tua yakin, namun anak-anak biasanya lebih optimis tentang masa depan. Para orang tua biasanya menjawab getir ‘terserah anak-anak’, namun kalau ditanya lebih jauh fantasi hidup enak adalah ‘anak bisa jadi PNS’. Entah pegawai, guru, polisi, atau tentara.
Elit ‘Soemanto’ di NTT
Nama Soemanto sempat tenar di jagad media Indonesia. Seorang lelaki dengan mata besar melotot bertugas membongkar makam dan memakan mayat. Apakah ia mengunyah atau mencabik tentu tidak perlu kita tanyakan.
Namun, watak Soemanto manusia pemakan jenasah sebenarnya merupakan watak dasar elit NTT. Kematian beruntun puluhan para manusia perantau pencari kerja, tidak mampu menggerakan para ‘laki-laki hebat’ di kursi kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Bahkan fakta koran yang menyebutkan ratusan orang diperdagangkan setiap tahun pun tidak membuat mereka memalingkan wajah?
Namun anehnya mereka bisa sedemikian mudah tergerak untuk saling mengucapkan selamat ulang tahun meggunakan surat kabar, dengan menggunakan nama instansi dengan duit negara pula. Tak hanya itu kebiasaan buruk birokrat NTT, mereka juga gemar memasang wajah di baliho berukuran besar. Padahal di depan mata kemiskinan ganas menampakan wajah dengan teramat jelas. Entah anak jalanan yang masih mengais rupiah jelang tengah malam; entah perempuan mati dalam peti tanpa nama dan alamat jelas; entah anak-anak yang kehilangan orangtua karena pergi merantau.
Kalau Soemanto, “ia” disebut sakit jiwa. Tapi bagaimana menyebut peristiwa ini, ketika secara kolektif kita tidak merasakan ini sebagai sebuah persoalan? Mulai dari keluarga dekat hingga tokoh agama semua mendapatkan peran. Saat pelantikan pejabat, rutinitas pasti adalah keluarga mempersiapkan pesta, dan kitab suci diangkat oleh imam. Seperti dalam pesta dentuman musim dengan lagu berbahasa asing bertalu dengan kencang dan orang bergembira tanpa harus mengerti, seperti itu pula kitab suci diperlakukan. Isinya tak penting, ritusnya lah yang penting. Belum ada cerita seorang imam mengaku dosa karena telah terlibat dalam ritus semacam ini.
Tapi sudah lah ini bukan persoalan transenden, apalagi soal keselamatan. Di NTT agama-agama Abrahamik ikut tenggelam dalam struktur klan. Setiap keluarga punya imam masing-masing. Setiap keluarga punya pejabat masing-masing. Setiap golongan agama punya pejabatnya masing-masing. Tidak peduli bagaimana kualitas mereka, yang penting itu ‘orang kita’. Jika butuh lampu jalan tinggal pindahkan, jika butuh semen 30 zak untuk bangun kamar mandi di rumah ibadah pun tinggal bikin proposal. Bagaimana mungkin kita menyebut ini ‘lingkaran setan’ ketika melibatkan ‘yang kudus’?
Mereka yang pergi
Pertanyaannya bagaimana dengan nasib mereka yang tak punya pejabat dalam keluarganya? Apakah tinggal di kampung merupakan pilihan? Anak-anak NTT sekarang ‘tidak tahan’ tinggal di kampung. Konsep tentang pekerjaan berubah. Konsep bekerja sangat terkait dengan kepemilikan uang tunai.
Ini pun tidak mengherankan, sejak kecil fantasi tentang orang hebat lekat dengan gambar orang berduit. Gambar paling ideal yang tergambar dalam masyarakat kita adalah menjadi pegawai. Entah kerja apa di kantor, yang pasti tiap bulan gaji jelas diterima. Fantasi semacam ini muncul sejak kecil, dan akan menjadi getir pada waktunya. Jadi jika ada anggota keluarga yang ingin menjadi pejabat, harus didukung, karena itu terkait penguasaan sumber daya. Seluruh anggota klan harus ‘muku’.
Salah satu dosa paling besar yang dilakukan oleh elit di provinsi (baca: republik) ini adalah memberikan pendidikan yang berkualitas buruk untuk anak-anak kita. Contohnya di provinsi yang sekarat semacam NTT, dana pendidikan tidak diperhatikan.
Para pejabat tidak peduli bagaimana nasib guru yang tidak menerima gaji selama sekian bulan akibat perubahan pos anggaran. Andaikan roti dan madu bisa turun dari langit, tentu anak guru tidak kelaparan. Apakah ada pejabat berempati dengan para guru yang kelaparan dan tidak mampu membayar kontrak kamar dengan ‘membagi gajinya’ atau cari akal agar para guru tak merana?
Empati kita cenderung mengering. Setiap orang berlomba melihat ke atas, dan lupa melihat yang terkapar. Anak-anak para elit disekolahkan di sekolah terbaik. Sebaliknya anak-anak rakyat jelata bersekolah apa adanya. Gambaran awal tentang modernitas terbangun lewat sekolah, seburuk apa pun sekolah itu.
Di sekolah yang gaji guru minim. Di sekolah yang gaji guru setengah tahun baru tiba. Di sekolah swasta yang tetap ‘beriman’ dengan teguh meskipun pemerintah ingin melupakan budi baik mereka. Di sekolah yang gurunya diadakan dengan konsep ‘tiada rotan akar pun jadi’. Di sekolah yang kurikulumnya mencabut anak-anak ini dari tanah-tanah sendiri. Di sekolah kampung yang untuk print buku pelajaran via e-book adalah kekonyolan yang pahit. Di sekolah yang guru-gurunya stress gaji kecil dan terlambat, bisa dibayangkan dampaknya untuk anak-anak.
Mungkinkah sekian persoalan sosial ini menjadi agenda para elit-elit hebat, para laki-laki narsis yang hobi memasang wajah di baliho sepanjang jalan via dolorosa? Jawabannya sudah jelas ‘tidak’. Bahkan mungkin berdoa meminta hujan jauh lebih masuk akal. Hujan turun, dan bibit tumbuh. Sementara orang baik dalam sistem dicabut sejak masih berbentuk tunas.
Semua sudah ada
Di pojok kota besar hingga di kampung adat salah satu kritik sosial yang muncul adalah ‘buat apa sekolah semua sudah ada, presiden sudah, gubernur sudah ada, bupati sudah ada’. Sepintas ucapan ini dianggap tak ada artinya. Namun jika kita meluangkan waktu untuk mendengar lebih jauh maka konsep ‘keterasingan sosial’ (social exclusion) pun muncul.
Aspek-aspek yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam wajah moderen, amat terkait dengan pengelompokan elit. Jadi bagi anak-anak yang masih sempat melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi, untuk masuk dalam kelompok elit mapan (baca: bergaji bulanan) maka syarat utamanya bukan prestasi, tetapi ‘kenal siapa’.
Wajar orang berujar ‘buat apa sekolah’. Sebab ketika sampai pada tangga tertinggi pun tidak ada jaminan bahwa ‘sukses ada di tangan’. Bukan karena anak malas sekolah, atau malas jalan kaki maka anak berhenti sekolah, tetapi karena gambaran pahit terbaca terlalu jelas di depan mata. Sekolah hanya sekedar menunda kekalahan yang pasti. Karena nepotisme merupakan elemen proses berbagi harta jarahan. Entah teman, entah bini, entah keluarga dipasang dalam jabatan publik. Urat malu kita putus.
Coba cek elit di NTT di kota berapa biji yang anaknya sekolah di SD negeri? Di desa kebalikannya, SD negeri bergizi sedangkan SD swasta sekarat. Guru negeri pun diancam untuk dicabut. Nasib Madrasah di bawah Departemen Agama masih lebih baik. Namun dalam konteks NTT sekolah missi dan zending saat ini ada dalam posisi ‘pikul salib’.
Pendidikan di sekolah negeri seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Konsep pembangunan memang bergeser mengikuti irama pasar. Dulu pendidikan moderen datang dengan pemahaman manusia lah yang harus dibangun. Sekarang lain, jembatan antar pulau lah yang harus dibangun. Entah manusia bodoh, kemampuan baca tulis rendah, atau kurang gizi itu bukan prioritas.
Selama masyarakat kita masih menganggap bahwa ‘figur-figur Soemanto’ lah yang menjadi wajah orang baik, dan orang di sekeliling aktif menadahkan tangan minta jatah, kita tidak bergeser kemana-mana. Selama kita membiarkan Yang Maha Kuasa bekerja sendirian, dan kita hanya meratap tentu perubahan juga tidak terjadi. Selama kita membiarkan anak-anak berhenti bermimpi di kelas satu SMP, kita adalah Soemanto.
Dalam kondisi semacam ini mereka yang selamat, selain mereka yang pergi dan hidup, adalah mereka yang mampu ada dalam lingkar pundi-pundi uang. Jika membaca struktur ekonomi NTT, pundi-pundi uang terbesar masih ada di tangan pemerintah. Wajar jika mereka yang tergusur total dan tidak mendapatkan tempat kemudian melontarkan pertanyaan ‘Untuk apa sekolah, jika semua sudah ada’. Sekolah dianggap sebagai tipuan massal. Ilusi yang lain.
Sudah saatnya kaum elit yang gemar berpesta kembang api, mengembalikan mimpi anak-anak NTT. Jika anak-anak anda diajar bermimpi, mengapa anak-anak lain dibiarkan mengais sampah, mendorong gerobak, menjadi pembantu, atau dibiarkan menjual koran hingga tertidur di pinggir trotoar sekedar untuk bisa bertahan hidup maupun untuk bayar uang sekolah. Mungkin mereka sedang bermimpi sambil bertanya pada Tuhan mengapa Soemanto mendapatkan pengikutnya, dan mengapa terang tak mampu mengurai kegelapan batin. Atau, mereka tak sempat bermimpi usai menjalani hari dan damai di Bumi tak lebih dari jeda menutup mata saat tubuh terbenam penat. (Dominggus Elcid Li)